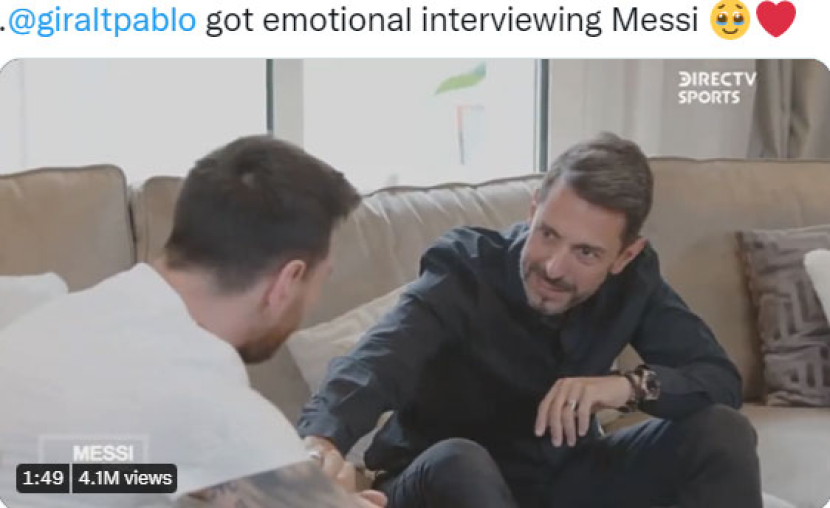Wartawan Bukan Hartawan

ruzka.republika.co.id--Kopi luak Bali masih hangat. Serbuknya cukup lembut. Wanginya menyengat. Baru seperempat saya seruput. Bukan lantaran perut tak bersahabat. Tapi, istri saya mendadak merajut. Ujuk-ujuk ngomel. Seperti petasan cabe rawit.
Bukan karena saya asik menikmati 'kemerdakaan'. Di teras rumah, jelang senja.
"Tetangga bikin sewot aja," umpat istri saya.
Saya hanya terperanga. 'Nyanyian jiwa' istri bisa saya terima. Kami 'difinah' orang kaya. Padahal kami hidup sederhana. Apa adanya. Bukan adanya apa. Tidak neko-neko. Kata orang tua dulu.
Saya juga tak bisa salahkan tetangga. Mereka hanya melihat kasat mata. Tahunya saya suka ke luar negeri. Jadi dianggap orang kaya. Maklum, saya tinggal di lingkungan yang padat. Dinding pun bisa berbunyi.
"Harusnya dapat arisan. Tapi, nama saya dimasukkan lagi. Katanya suaminya sering keluar negeri. Nggak butuh uang," cerita istri makin mangkel.
"Padahal saya lagi butuh buat bayar sekolah dan angsuran bulanan," cetusnya.
Saya jadi pendengar setia. Mau tertawa takut istri tambah murkah. Saya hanya mengelus dada. Dalam hati mengamini 'tuduhan' emak-emak rempong. Lain hal andai mereka tahu apa yang saya lakukan saat betugas ke luar negeri.
Saya keluar negeri bukan holiday. Bukan mencari kesenangan. Atau menghabiskan uang. Layaknya selebriti yang gemar cari sensasi. Saya keluar negeri lantaran tugas jurnalistik. Dari kantor tempat saya bekerja. Pekerjaan yang saya geluti lebih dari 30 tahun. Hingga hari ini. Profesi panggilan hati. Juga menantang. Masih terekam dalam memori saya.
Kali pertama kuliah di IISIP Lenteng Agung pada 1989. Pesan seorang dosen senior sangat dalam. "Jika ingin kaya jangan jadi wartawan, tapi hartawan. Wartawan cuma kaya akan pergaulan. Yang ingin kaya harta silakan keluar," kata dosen Pak Pur.
Saya memilih bertahan di ruangan. Karena saya tak pernah bercita-cita jadi orang kaya. Saya ingin hidup sederhana. Saya sadar kebahagiaan seorang wartawan adalah jika karyanya berguna dan bermanfaat bagi orang banyak.
Seperti kata Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari-- yang juga lulusan STP (sebelum berganti IISIP). Wartawan profesi yang mulia. Tidak lebih rendah dari seorang tukang becak dan tidak lebih tinggi dari menteri.
Maksudnya, wartawan bisa bergaul dengan segala lapisan masyarakat. Mulai dari orang biasa saja- pedagang asongan, tukang parkir- hingga pejabat negara. Bahkan pena wartawan bisa mengguncang dunia. Rangkaian pesan itu melekat di kepala.
Dan saya terbilang beruntung. Dipercaya meliput event besar. Mulai dari SEA Games, Asian Games, ParaGames, Piala Eropa hingga Piala Dunia. Kesempatan itu tak saya sia-siakan. Berbagai persiapan saya lakukan. Jauh-jauh hari. Biasanya 6 sebelumnya. Mulai dari pelajari budaya negara, demografi, ekonomi, bahasa, hingga event tersebut.
Andai mereka tahu. Tugas keluar negeri itu tidak mudah. Tak seperti mereka bayangkan. Beban menggunung di pundak. Saya harus membuat proyeksi. Mengejar target yang diproyeksikan kantor. Setiap hari harus menyisir jalan. Dari tempat penginapan.
Di pagi hari. Pulang larut malam. Bahkan bisa dini hari. Tergantung situasi liputan di lapangan.Bermodal map saya turun naik kereta. Acap antarkota. Karena kemp sebuah tim biasanya di pedalaman. Jauh dari keramaian kota. Pun venue pertandingan.
Kemudian dilanjutkan dengan jalan kaki. Bisa menempuh antara 3-5km. Belum lagi tas ransel di pundak. Laptop, kamera, buku, tape recorder, botol minum, serta peralatan 'perang' lainnya. Beratnya sekitar 10kg. Alaaamak... keringat, air mata dan darah tak terasa tumpah. Jalan panjang yang saya tempuh penuh rintangan. Harus bisa membaca situasi.
Terutama saat berhadapan dengan stewards. Acap bikin saya stres. Jika target yang diproyeksikan dari kantor tak tercapai. Saya harus mengganti figur alternatif untuk diwawancarai. Pun dilampirkan bukti foto dan rekaman.Belum lagi mempersiapkan tulisan. Mencari angle yang menarik. Wartawan dituntut 'liar' dalam berpikir.
Merangkai kata demi kata. Menggiring pembaca agar larut dalam kisah yang kita rangkum. Tentu ini tidak mudah. Cukup menguras energi dan pikiran. Tidur pun tak nyenyak. Maksimal 4 jam sudah bagus. Tapi suka atau tidak saya harus menikmati. Karena tuntutan pilihan profesi.
Sepanjang jalan saya mencoba membuat draft laporan. Jika tugas pertama selesai, lanjut berikutnya. Begitu seterusnya. Belum lagi diwajibkan bikin sisi lain dari sebuah event. Bisa soal sosial, budaya, ekonomi. Atau apapun yang menarik atau human.
Terkadang sisa kopi di pagi hari, saya seruput di malam hari. Saat kembali ke penginapan. Sambil mempersiapkan proyeksi esok pagi.Andai mereka tahu, tentu kopi Bali yang wangi itu tak tersisa saya seruput. Tak perlu tunggu dingin. Dan tak ada 'tuduhan' sebagai orang kaya.
Suryansyah/Warga Depok Pinggiran/Sekjen Siwo PWI Pusat 2018-2023