 Wisnu Dewa Wardhana
Wisnu Dewa Wardhana
Indonesia Negara Republik, Bukan Negara Siap Ndan
Politik | 2025-03-29 19:15:04
Belum genap enam bulan sejak Prabowo Subianto duduk di Istana Negara, protes mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat berulang terjadi di berbagai kota; tidak hanya itu, tagar #IndonesiaGelap sebagai representasi protes di media sosial terus tersemat dalam unggahan warganet yang peduli dengan tragisnya keadaan Indonesia. Namun, perlawanan tersebut seolah dianggap angin lalu oleh penguasa; kebijakan ugal-ugalan dan asal jadi terus diproduksi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yang terbaru, DPR bersama Pemerintah tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) meskipun penolakan publik terus bergaung di jalanan dan media sosial.
Terlepas dari substansi atau isi, satu hal yang perlu digarisbawahi: proses Revisi UU TNI tidak melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana wajarnya proses legislasi di negara demokrasi.
Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat
Pengertian demokrasi tidak sesederhana rutin mengadakan pemilu setiap lima tahun untuk memilih seorang pemimpin pemerintahan (Presiden) dan memilih sekian orang untuk mewakili rakyat di parlemen (DPR) lantas membiarkan orang-orang itu menentukan nasib sebuah negara. Pengertian demokrasi lebih fundamental dari itu.
Secara etimologis, kata 'demokrasi' berasal dari kata demokratia; demos berarti ‘rakyat’ dan kratos berarti 'kekuasaan', jadi demokrasi dapat diartikan sebagai 'kekuasaan rakyat' atau pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, demokrasi bermakna pemerintahan (kekuasaan) yang dijalankan secara bersama-sama oleh semua orang; unsur-unsur negara — seperti Presiden dan DPR — hanya pemegang mandat (dititipkan) untuk menjalankan kekuasaan tersebut.
Oleh karena itu, keterlibatan atau partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam negara demokrasi; suatu negara sah disebut negara demokrasi hanya jika ada ruang partisipasi bagi rakyat dalam proses bernegara. Pertanyaannya, bagaimana cara rakyat berpartisipasi di negara demokrasi?
Jika disederhanakan, mekanisme partisipasi rakyat di negara demokrasi dapat dibagi menjadi dua model, yaitu: 'demokrasi langsung' (direct democracy) dan demokrasi representatif (representative democracy). Dalam praktiknya, 'demokrasi langsung' berarti semua orang terlibat secara langsung dalam pembentukan kebijakan atau undang-undang; sementara itu, 'demokrasi representatif' pada praktiknya berarti rakyat memilih sejumlah individu sebagai wakil rakyat melalui pemilu untuk menjalankan tugas pemerintahan atas nama rakyat.
'Demokrasi Langsung'
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), salah satu filsuf politik yang meletakkan dasar-dasar teori demokrasi modern, adalah pemikir yang dikaitkan dengan model 'demokrasi langsung'. Di dalam buku The Social Contract (1762), Rousseau menulis:
"Sovereignty cannot be represented for the same reason that it cannot be alienated; and the will cannot be represented; Every law which the people in person have not ratified is invalid; it is not a law."
Menurut Rousseau, kedaulatan dan kehendak seluruh rakyat tidak dapat diwakilkan oleh sejumlah orang, hukum harus dibentuk oleh rakyat secara bersama-sama, rakyat harus terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan di negara demokrasi. Jika ditarik kepada konteks Indonesia saat ini, Rousseau barangkali akan mengolok-olok lembaga negara seperti DPR yang bertindak seolah-olah mewakili kehendak rakyat. Di dalam buku yang sama, Rousseau mencatat: "The English nation thinks that it is free, but is greatly mistaken, for it is so only during the election of members of Parliament; as soon as they are elected, it is enslaved and counts for nothing."
Rousseau mengejek model demokrasi perwakilan Inggris, bahwa rakyat Inggris telah ditipu oleh wakil rakyatnya di parlemen (DPR), para wakil rakyat tersebut hanya membutuhkan rakyat ketika pemilu; setelah mereka terpilih, rakyat tidak dianggap, diperbudak, dan kepentingan rakyat tidak diperhitungkan lagi.
Negara kelahiran Rousseau, Swiss, merupakan contoh negara yang masih menerapkan 'demokrasi langsung' sampai hari ini. Walaupun Swiss memiliki perwakilan rakyat dan tidak semua hukum mewajibkan persetujuan rakyat, Swiss rutin melakukan referendum untuk meminta persetujuan rakyat terkait kebijakan atau undang-undang tertentu yang akan berlaku.
Model 'demokrasi langsung' memang tampak ideal, hanya saja ada beberapa kekurangan dari model demokrasi ini, misalnya persoalan efisiensi. Model 'demokrasi langsung' hanya cocok diterapkan di negara kecil seperti Swiss; untuk negara sebesar Indonesia, model demokrasi ini akan memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit, sebab perlu persetujuan rakyat banyak sebelum suatu kebijakan diterapkan. Selain itu, model 'demokrasi langsung' memungkinkan terjadinya diskriminasi terhadap kelompok minoritas, contoh kasusnya adalah pemberlakuan larangan pemakaian penutup wajah — termasuk burqa atau cadar — di Swiss setelah 51.2% rakyat Swiss memilih lewat referendum (Associated Press News 2021).
Rousseau sendiri mengakui bahwa model 'demokrasi langsung' akan berjalan dengan baik jika memenuhi beberapa syarat, satu di antaranya ialah ketiadaan kesenjangan ekonomi. Jika kesenjangan jumlah penduduk kaya dan miskin masih tinggi, ada kecenderungan kelompok miskin menjual suaranya dalam pemilihan (Wolff 2006), artinya 'demokrasi langsung' tidak akan bermanfaat seperti yang diharapkan.
Demokrasi Representatif (Perwakilan)
Oleh karena 'demokrasi langsung' tampak terlalu ideal dan sukar diterapkan, kebanyakan filsuf dan pemikir teori demokrasi — seperti John Locke, Montesquieu, Thomas Paine, James Madison, dan John Stuart Mill — cenderung menganjurkan mekanisme demokrasi representatif untuk mengelola demokrasi. Di dalam Considerations on Representative Government (1861) John Stuart Mill menulis:
"But since all cannot, in a community exceeding a single small town, participate personally in any but some very minor portions of the public business, it follows that the ideal type of a perfect government must be representative."
John Stuart Mill menyadari bahwa tidak semua orang memiliki waktu untuk mengurusi hal-hal kenegaraan, maka sistem pemerintahan yang ideal adalah demokrasi representatif; rakyat memilih para wakilnya untuk menjalankan pemerintahan demi kepentingan bersama. Meski begitu, Mill tidak serta-merta mengabaikan keterlibatan rakyat dalam demokrasi perwakilan.
' that the only government which can fully satisfy all the exigencies of the social state, is one in which the whole people participate [and] that any participation, even in the smallest public function, is useful."
Menurut Mill, satu-satunya cara agar pemerintah bisa mewujudkan kesejahteraan ialah dengan melibatkan rakyat dalam proses bernegara; sekecil apa pun keterlibatan rakyat akan bermanfaat untuk kelangsungan negara.nBerbeda dengan Rousseau, Mill justru menganggap demokrasi perwakilan sebagai model demokrasi terbaik. Dalam pandangan Mill, tindakan seseorang cenderung didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok (Thompson 1976), karena itu jika 'demokrasi langsung' yang digunakan maka kepentingan mayoritas akan diutamakan dibandingkan hak-hak minoritas. Kasus pelarangan penutup wajah di Swiss adalah contoh kasus buruk dari penerapan 'demokrasi langsung'.
Sebagai tambahan saja, di dalam teori demokrasinya, Mill juga mengajukan sebuah konsep yang menarik tetapi kontroversial, yakni konsep Plural Voting. Dalam pengertian sederhana, Plural Voting adalah kebalikan dari prinsip 'One Man, One Vote' (satu orang, satu suara); Plural Voting memungkinkan seseorang yang berkompeten memiliki lebih dari satu suara pada pemilihan umum (pemilu). Inggris adalah contoh negara yang pernah menerapkan konsep Plural Voting dalam pemilu; sampai tahun 1948, seseorang yang memiliki gelar sarjana di Inggris mendapat lebih dari satu hak suara pada pemilihan anggota parlemen (DPR) (Thompson 1976).
Konsep Plural Voting memang kontroversial dan banyak ditolak karena alasan keadilan, tetapi prinsip 'One Man, One Vote' juga tidak lebih baik, justru dalam banyak kasus prinsip 'One Man, One Vote' malah memperburuk demokrasi, karena itu konsep Plural Voting Mill patut untuk dibicarakan kembali. Hanya sedikit pemikir demokrasi dewasa ini yang menyokong konsep Plural Voting, dua di antaranya adalah Robin Harwood (More Votes for Ph.D.'s.) dan Thomas Mulligan (Plural Voting for the Twenty-First Century). Tulisan dua pemikir tersebut tentang Plural Voting layak dibaca dan direnungkan, bahkan diterapkan suatu saat nanti. Apakah pantas suara seorang profesor yang melakukan riset sebelum memilih dalam pemilu dihitung sama dengan suara anak SMA yang memilih berdasarkan gemoy-nya goyangan calon Presiden di TikTok?
Saat ini, hampir semua negara demokrasi di dunia memilih demokrasi representatif dengan prinsip 'One Man, One Vote' sebagai model demokrasi untuk menjalankan pemerintahannya, termasuk Indonesia.
Omong Kosong Demokrasi Perwakilan di Indonesia
"Indonesia adalah negara demokrasi!" Pernyataan itu berdasar pada hukum tertinggi Indonesia, UUD 1945 pasal 1 ayat (2) berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Lebih spesifik lagi, sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah memilih demokrasi perwakilan (representatif) sebagai model demokrasi Indonesia, hal tersebut tercermin lewat sila keempat Pancasila: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Sayangnya, demokrasi perwakilan di Indonesia hanya istilah tanpa makna berarti; mereka yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru bertindak tanpa memedulikan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia, DPR bersama Presiden adalah pemegang mandat untuk mewakili rakyat dalam proses pembentukan undang-undang sebagaimana bunyi Pasal 20 UUD 1945, kendati begitu DPR dan pemerintah tetap diwajibkan berdiskusi, mendengar, serta mempertimbangkan pendapat masyarakat secara serius.
UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 huruf (g) secara tegas menyatakan bahwa salah satu asas pembentukan undang-undang di Indonesia adalah 'asas keterbukaan' yang erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Hal tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 96 Ayat (1) UU No. 13/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang UU No. 12/2011 yang berbunyi: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan".
Penyampaian aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang juga diatur secara teknis dalam Peraturan presiden No. 87/2014 dan No. 76/2021, serta Peraturan DPR No. 2/2020. Permasalahannya kemudian, dalam banyak kasus, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang seakan-akan tidak berarti atau sekadar formalitas; UU Cipta Kerja, UU IKN, dan Revisi UU KPK adalah beberapa contoh undang-undang yang tetap disahkan DPR meskipun minim partisipasi publik dan bertentangan dengan kehendak masyarakat. Dengan demikian, tidak berlebihan jika menyebut partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia hanya omong kosong, khususnya sejak kepemimpinan Joko Widodo si raja-rajaan Jawa.
Revisi UU TNI merupakan contoh mutakhir pengabaian partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.
Mentalitas "Siap, 'Ndan!" dalam Revisi UU TNI
Revisi UU TNI bermasalah dalam banyak hal, selain substansi atau isi, masalah mendasar dari revisi undang-undang tersebut adalah proses pembentukannya. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menilai Revisi UU TNI bermasalah karena tidak sejalan dengan cita-cita reformasi, tidak sesuai konstitusi, dan cacat prosedur legislasi. Ada tiga catatan kritis dari PSHK, salah satunya adalah pembahasan Revisi UU TNI yang tidak transparan sehingga menyumbat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya (PSHK 2025).
Selain itu, proses Revisi UU TNI berlangsung sangat cepat dan terkesan buru-buru. Berdasarkan keterangan dari DPR, Revisi UU TNI baru dimulai pada tanggal 13 Februari 2025 ketika DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto, kemudian dalam lima hari — tepatnya tanggal 18 Februari 2025 — pembahasan revisi undang-undang tersebut secara resmi dimulai di DPR, dan pada tanggal 27 Februari 2025 Komisi I DPR telah membentuk Panitia Kerja untuk membahas Revisi UU TNI. Seterusnya, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat sebanyak empat kali pada tanggal 3, 4, 10, dan 18 Maret 2025 sebagai bentuk partisipasi publik (Thea 2025). Akhirnya, di tengah penolakan publik yang masif, pada tanggal 20 Maret 2025, hanya dalam 36 hari sejak DPR menerima surat dari Presiden, Revisi UU TNI disahkan di rapat paripurna DPR. Karena itu, dapat dimaklumi ketika masyarakat bertanya, "Ada apa dengan Revisi UU TNI?"
Masalah lain adalah pembahasan Revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup dan terkesan sembunyi-sembunyi. Salah satu rapat pembahasan Revisi UU TNI dilaksanakan DPR di sebuah hotel mewah di Jakarta pada akhir pekan. Hal ini menjadi polemik setelah tiga aktivis Koalisi Masyarakat Sipil mendobrak masuk ke dalam rapat tersebut dan tidak lama kemudian pasukan super elite TNI (Koopssus) diturunkan untuk berjaga di sekitar hotel demi keamanan rapat. Andaikata polisi sebagai aparat sipil yang mengawal rapat tersebut mungkin masih masuk akal, tetapi, jika pasukan super elite TNI sampai harus diturunkan hanya karena tiga orang sipil tanpa senjata api masuk tanpa izin ke dalam rapat, apakah masuk akal? Karena itu, dapat dimaklumi ketika masyarakat bertanya, "Ada apa dengan Revisi UU TNI?"
Keanehan berikutnya, yaitu undang-undang tersebut tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang memuat RUU prioritas 2025 serta tidak tercantum dalam 18 rancangan undang-undang prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Revisi UU TNI baru diajukan ke dalam Prolegnas oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 7 Februari 2025 yang diikuti oleh surat Presiden tertanggal 13 Februari 2025 kepada DPR, kemudian dalam hitungan hari saja segera direspons DPR dengan memasukkan Revisi UU TNI dalam Prolegnas 2025.
Maka dari itu, sejumlah masyarakat mempertanyakan urgensi Revisi UU TNI sampai harus diprioritaskan serta dipaksakan masuk ke dalam Prolegnas 2025. Lebih-lebih, tidak ada hal mendesak yang membuat UU TNI harus segera direvisi. Sebagai catatan saja, UU Masyarakat Adat yang lebih mendesak sampai saat ini masih dibahas di DPR, padahal rancangan undang-undang tersebut telah diajukan sejak tahun 2009 dan sudah berulang kali masuk Prolegnas. Kurang lebih 16 tahun RUU Masyarakat Adat terendap di DPR tanpa pernah disahkan, tetapi Revisi UU TNI hanya dalam hitungan minggu sudah disahkan DPR. Lagi-lagi, dapat dimaklumi ketika masyarakat bertanya, "Ada apa dengan Revisi UU TNI?"
Pada akhirnya, Revisi UU TNI menunjukkan satu hal, mentalitas "Siap, 'Ndan!" dalam proses bernegara di Indonesia. Mentalitas "Siap, 'Ndan!" erat kaitannya dengan budaya militer, yakni ketika komandan memerintah, tidak ada jawaban lain selain "Siap, 'Ndan!". Surat Presiden yang buru-buru direspons DPR memperlihatkan bahwa proses legislasi di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, proses revisi UU TNI tampak seperti proses legislasi di negara otoriter yang dipimpin seorang diktator. Dalam konteks ini, sekalipun suara rakyat di jalanan dan media sosial menolak, ketika Prabowo bertitah, DPR hanya bisa bilang, "Siap, 'Ndan!".
Terkait pemenuhan partisipasi masyarakat, Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan hanya empat kali (tanggal 3, 4, 10, dan 18 Maret 2025) sebetulnya tidak layak disebut sebagai partisipasi masyarakat, sebab UU TNI yang direvisi dampaknya akan sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat sipil. Maka itu, cukupkah Rapat Dengar Pendapat dilakukan hanya empat kali dalam kurun waktu dua minggu? Tentu tidak. Rapat Dengar Pendapat tersebut hanya formalitas untuk memenuhi unsur partisipasi masyarakat yang diwajibkan undang-undang.
Lebih dari itu, kekhawatiran masyarakat sipil terkait kembalinya dwifungsi TNI seharusnya direspons lebih serius oleh DPR, mengingat rakyat Indonesia memiliki trauma masa lalu terhadap dwifungsi ABRI (TNI). Tidak boleh dilupakan bahwa tentara termasuk aktor yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Bahkan, ketika kekuasaan militer di ranah sipil sudah dipersempit, TNI masih sering melakukan pelanggaran HAM berat terhadap rakyat sipil.
Pembantaian Biak di Papua dan Peristiwa Alastlogo di Pasuruan adalah dua contoh kebiadaban TNI pasca-reformasi. Belum lagi arogansi TNI yang merasa sebagai manusia superior sehingga kerap bertindak seenaknya terhadap rakyat sipil, kasus yang paling baru ialah penembakan pemilik rental mobil oleh oknum anggota TNI pada 2 Januari 2025.
Sebagai rangkuman, Revisi UU TNI bermasalah dalam proses pembentukannya karena berlangsung terlalu cepat, terkesan buru-buru, dan tampak dipaksakan, serta pemenuhan partisipasi publik yang dilakukan pada dasarnya tidak lebih dari formalitas belaka. Dengan demikian, reaksi masyarakat sipil melalui demonstrasi seharusnya dapat diwajarkan dan tidak pantas disebut berlebihan.
Demokrasi 'Omon-Omon' Indonesia
Demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, merujuk pada riset The Economist Intelligence Unit (EIU), Demokrasi Indonesia pada tahun 2024 masih terkategorikan Flawed Democracy (Demokrasi Cacat) dan secara umum angka Indeks Demokrasi Indonesia terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Nilai Indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2024 adalah 6,44 (dari 10), berada di peringkat 59 dari 167 negara — turun tiga tingkat dari tahun sebelumnya.
Ada banyak alasan di balik memburuknya demokrasi Indonesia, salah satunya adalah kekuasaan yang terpusat pada individu atau kelompok tertentu, dan hal itu erat kaitannya dengan ketiadaan partisipasi masyarakat. Artinya, masalah demokrasi Indonesia bersifat fundamental dan mengkhawatirkan, sebab esensi demokrasi itu sendiri adalah pemerintahan rakyat; tanpa keterlibatan rakyat, demokrasi tidak mungkin ada. Jean-Jacques Rousseau dan John Stuart Mill memang banyak berbeda pandangan dalam teori demokrasi, tetapi mereka sepakat bahwa demokrasi mewajibkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, meminjam istilah Prabowo Subianto, tanpa partisipasi masyarakat, demokrasi tidak lebih dari sekadar 'omon-omon' (ngomong-ngomong omong kosong).
Proses Revisi UU TNI hanya satu fenomena di permukaan yang menampakkan buruknya demokrasi perwakilan di Indonesia. DPR sebagai perwakilan rakyat, nyatanya tidak mewakili rakyat; Revisi UU TNI dengan gampangnya sah di rapat paripurna DPR, suara-suara penolakan terhadap undang-undang tersebut tidak dianggap ada. DPR justru memperlihatkan mentalitas "Siap, 'Ndan!", mengiyakan keinginan Presiden lantas mengabaikan keinginan rakyat; padahal, dasar negara (Pancasila), hukum tertinggi (UUD 1945), sampai peraturan yang bersifat teknis, sangat jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi perwakilan yang mewajibkan partisipasi masyarakat. Indonesia bukan negara "Siap, 'Ndan!" yang didirikan untuk menuruti keinginan Prabowo dan kawan-kawan.
Kelakuan Presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan rakyat sama saja dengan DPR. Kurang dari enam bulan sejak dilantik, tidak sedikit kebijakan ajaib pemerintahan Prabowo yang bertentangan dengan kehendak rakyat, mulai dari efisiensi, pengunduran jadwal pengangkatan CPNS, bahkan sejak dilantik pun, 'kabinet gendut' Prabowo sudah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Ketiadaan kekuatan politik penanding (oposisi) yang mengawasi pemerintah dalam proses bernegara bisa jadi sebab pemerintah leluasa dalam membentuk kebijakan-kebijakan ajaib tersebut. Akan tetapi, masalah demokrasi Indonesia sudah berakar sejak pemilu. Di sinilah pendapat Rousseau relevan, bahwa rakyat Indonesia ditipu lagi untuk kesekian kali oleh Presiden dan DPR. Setelah pemilu lewat dan mereka terpilih, rakyat tidak dianggap, diperbudak, dan kepentingannya tidak diperhitungkan lagi. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apakah Indonesia akan lebih baik jika menerapkan model 'demokrasi langsung'? Atau, mempertahankan demokrasi perwakilan tetapi berprinsip Plural Voting?
Demokrasi langsung ataupun demokrasi representatif tidak berkaitan dengan kemunduran demokrasi di Indonesia. Semua aturan hukum tentang partisipasi masyarakat sudah jelas, masalahnya adalah tidak adanya keinginan baik (political will) para penguasa di negeri ini untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Mereka justru bertindak seolah-olah yang paling pintar; apa pun kebijakan pemerintah, rakyat harus menerima; seolah-olah Indonesia adalah negara "Siap, ‘Ndan!".
Akhir kata, kurang dari enam bulan Prabowo berkuasa, menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi agaknya terlalu berlebihan, sebab demokrasi Indonesia dalam praktiknya hanya 'omon-omon' belaka.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.


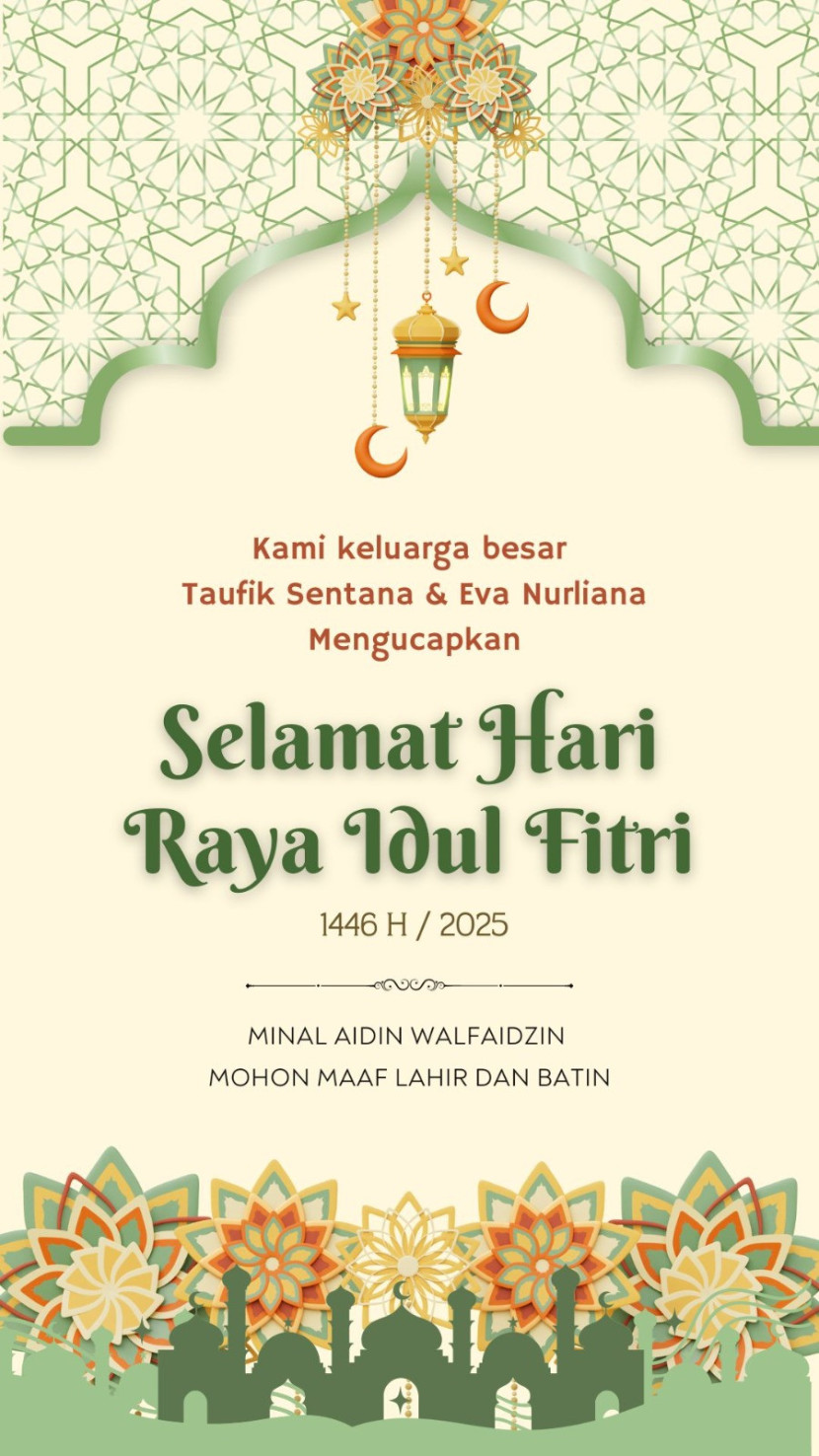
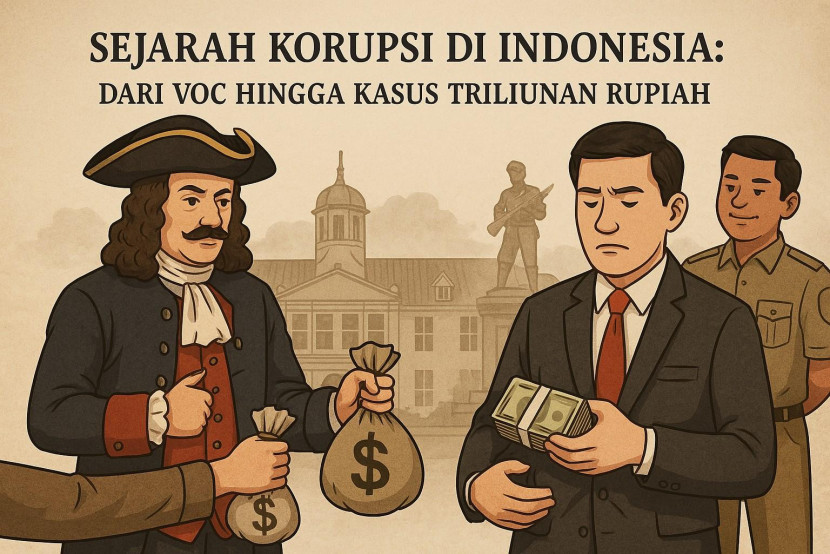






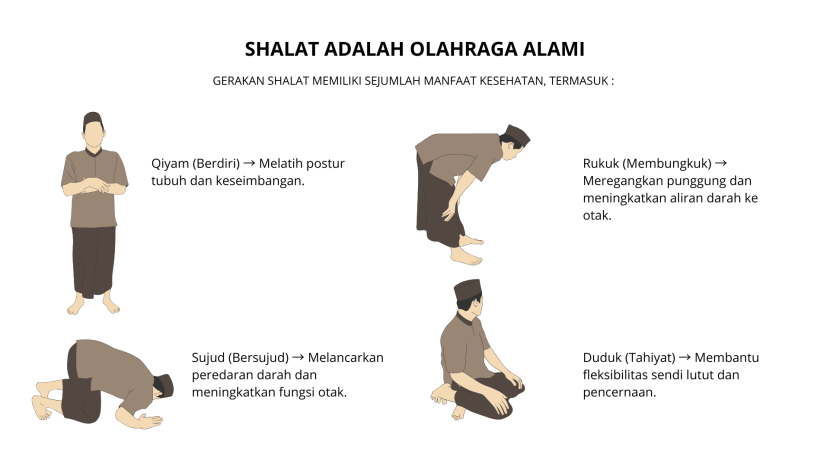
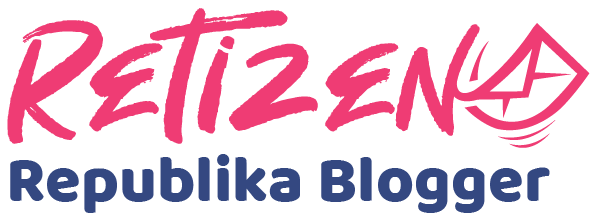
Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook